Oleh Laurens Minipko
Pendahuluan
Tulisan ini merupakan upaya merefleksikan sejarah Mimika—dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Mimika ke-29—berdasarkan catatan etnografis antropolog Pater Jan Boelaars, MSC, dalam buku Met Papoea’s Samen op Weg, khususnya Bab VII “De Mimika en het Bergland”.
Sejarah Mimika bukan semata kisah aliran sungai, pesta adat, atau perpindahan kampung. Ia juga sejarah tentang bagaimana orang luar menamai, mendefinisikan, dan menata tubuh serta kehidupan orang Mimika. Dari catatan misionaris Belanda awal abad ke-20 hingga laporan antropolog, Mimika tampil bukan sekadar ruang geografis, melainkan medan tafsir yang diperebutkan.
Nama sebagai Kuasa
P. Drabbe MSC, seorang misionaris Belanda, memperkenalkan istilah “Kamoro” sebagai nama bahasa dan etnis. Nama ini kemudian dipakai luas dalam literatur akademik dan birokrasi, tetapi tak pernah benar-benar diakui orang Mimika sendiri. Mereka lebih memilih menyebut diri “Orang Mimika” atau Mimika wee, istilah yang melekat pada sungai dan tanah yang menjadi sumber kehidupan.
Di sini tampak jelas bahwa nama berfungsi sebagai alat kuasa: bukan sekadar label, melainkan cara orang luar mengatur pandangan terhadap masyarakat setempat.
Tubuh dan Tafsir Orang Luar
Pater Neijens MSC dalam catatan etnografinya menggambarkan perempuan Mimika sebagai sosok “menakutkan” ketika menghadapi orang asing. Gambaran ini lebih mencerminkan keterkejutan pendatang ketimbang realitas sehari-hari perempuan Mimika.
Tubuh perempuan, dalam catatan kolonial dan aparatur, kerap menjadi ruang proyeksi ketakutan dan fantasi orang luar. Kuasa kolonial hadir bukan hanya lewat senjata atau misi agama, melainkan juga lewat tulisan yang menstigma tubuh orang Mimika—dengan dampak nyata pada sikap dan perlakuan terhadap perempuan Mimika.
Struktur Sosial: Komplementaritas
Menengok ke dalam kehidupan orang Mimika sendiri, tampak sebuah visi sosial yang unik dan sakral: laki-laki dan perempuan dipahami dalam kerangka komplementer. Mereka berbeda, bahkan kadang berseberangan, tetapi saling melengkapi.
Perempuan memegang peran vital dalam penguasaan tanah, kebun sagu, dan wilayah penangkapan ikan. Hak-hak itu diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, memperlihatkan adanya agensi yang kuat.

Sebaliknya, laki-laki mengklaim peran “pencipta” dalam upacara inisiasi. Mereka menyatakan bahwa sumber kehidupan berasal dari mereka, sehingga merekalah yang “memahat” manusia baru. Tafsir ini berbeda dengan pengalaman biologis perempuan, namun tetap hidup berdampingan sebagai narasi budaya yang unik dan luhur.
Antara Tafsir dan Kekuasaan
Dari sini dapat ditarik benang merah: sejarah Mimika adalah sejarah tafsir yang bertemu dan bertabrakan. Tafsir orang luar menamai, menilai, bahkan menstigma; sementara tafsir orang Mimika sendiri membangun dunia sosialnya dengan logika komplementer—antara laki-laki dan perempuan, pantai dan pedalaman, tradisi dan perubahan.
Maka persoalan Mimika tidak sesederhana soal “nama” atau “adat”. Ia adalah soal kuasa atas tafsir: siapa yang berhak menamai, siapa yang berhak menentukan makna tubuh, tanah, bahasa, dan sejarah. Kolonialisme hadir bukan hanya dalam penguasaan politik dan ekonomi, tetapi juga dalam ranah bahasa, simbol, dan pengetahuan.
Penutup
Hari ini, ketika “Kamoro” atau “Mimika” menjadi nama resmi dalam dokumen negara dan laporan perusahaan, kita layak bertanya: apakah kita sedang mengulangi kuasa kolonial dalam bentuk baru? Ataukah sudah saatnya mengembalikan hak orang Mimika untuk menafsirkan dirinya sendiri dengan bahasa, tubuh, dan sejarah mereka?
Mimika, dengan sungai-sungainya yang tak henti mengalir, seakan memberi pesan: tafsir boleh datang dan pergi, tetapi kehidupan orang Mimika tetap berakar pada tanah, sagu, ritus adat, sejarah, dan kosmologi yang tak bisa sepenuhnya dipahami oleh nalar dan pena orang lain. (*)
Jumlah Pengunjung: 6
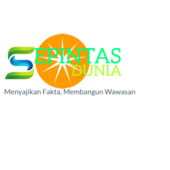
 2 months ago
98
2 months ago
98

















































